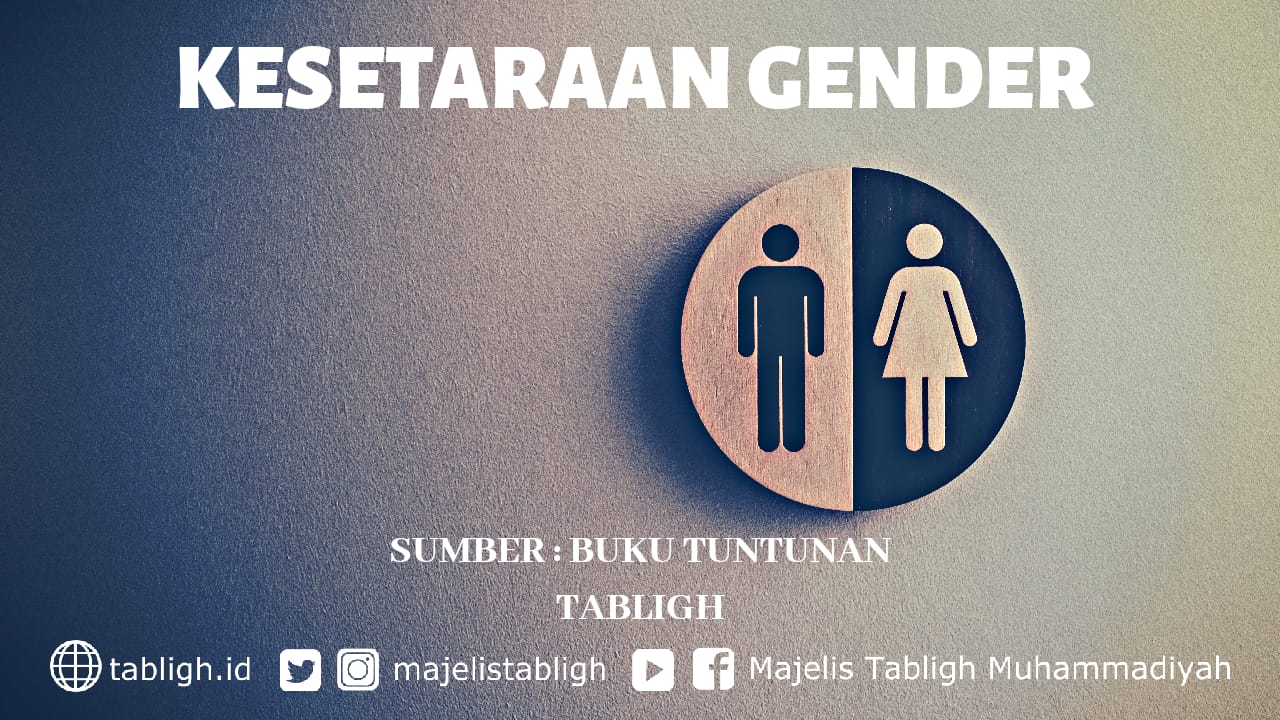
Keadilan Gender : Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam
Oleh: Adian Husaini
Anggota Majelis Tabligh & Dakwah Khusus PP Muhammadiyah
Periode 2005-2010
”Amerika Serikat juga memberikan pendanaan kepada berbagai organisasi Muslim dan pesantren untuk mengangkat persamaan jender dan anak perempuan dengan memperkuat pengertian tentang nilai-nilai tersebut di antara para pemimpin perempuan masyarakat dan membantu demokratisasi serta kesadaran jender di pesantren melalui pemberdayaan pemimpin pesantren laki-laki dan perempuan.” (Program Amerika Serikat dalam mengembangkan paham kesetaraan gender. Lihat:
http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/indonesia_Laporan_deplu-AS.html ).
“Mukhthi’un man zhanna yawman anna li-asysya’labi diinaa —Adalah keliru, orang yang menyangka, bahwa suatu hari, serigala punya agama. (Pepatah Arab).
Pada Hari Jumat, 18 Maret 2005, dunia Islam disuguhi satu tontonan yang ganjil. Ketika itu, Amina Wadud, seorang feminis liberal, memimpin shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Wadud, seorang profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi imam sekaligus khatib, dalam salat Jumat yang diikuti sekitar 100 jamaah, laki-laki dan wanita. Shaf laki-laki dan wanita bercampur. Sang Muazin pun seorang wanita, tanpa kerudung.
Amina Wadud adalah seorang feminis. Ia menulis buku berjudul Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Quran menurut Perempuan, (Jakarta: Serambi, 2001). Melalui bukunya, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan al-Quran ‘model klasik’ yang dinilainya menghasilkan tafsir yang bias gender, alias menindas wanita. Ia tidak menolak al-Quran. Tetapi, yang dia lakukan adalah membongkar metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir gaya baru yang dia beri nama “Hermeneutika Tauhid”. Dengan metode tafsir gaya baru itu – meskipun al-Qurannya sama – maka produk hukum yang diperoleh juga sangat berbeda. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah “relativisme tafsir.” Kata Wadud, “Tidak ada metode tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif.” 1
Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis, misalnya, adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS 4:34). Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Kaum aktivis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga (rabbatul bayt). Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga adalah merupakan konsep budaya, bukan hal yang kodrati. Amina Wadud menulis tentang hal ini:
“Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita.” 2
Amina Wadud adalah salah satu contoh feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan mengubah konsep-konsep Islam tentang wanita untuk disesuaikan dengan nilai-nilai modern yang berlaku di dunia saat ini. Dalam perspektifnya, banyak hukum Islam yang diterapkan selama ini di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Karena itulah, dia ingin membuat konstruksi hukum baru dalam perspektif dan kepentingan perempuan. Karena itulah, bukunya diberi judul: Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, atau dalam bahasa Indonesianya: Quran Menurut Perempuan.
Paham ‘kebencian’
Jika ditelusuri, ide “gender equality” (kesetaraan gender) yang dianut oleh Wadud dan kaum feminis lainnya, bersumber dari pengalaman Barat dengan pandangan hidup sekular-liberal. Menurut Ratna Megawangi, ide kesetaraan gender ini bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kiaum tertindas, dan sebagainya. 3
Menurut Ratna, agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak. 4
Perspektif Marxis inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kacamata kecurigaan, bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadits dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Para pendukung ide gender equality menolak penafsiran yang bersifat tafadul, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning telah menerbitkan satu buku bertajuk “Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn” yang memperjuangkan gender equality dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut mereka, QS an-Nisa:34, harus diartikan, bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut para pendukung ide kesetaraan gender ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita. 5
Semangat kebencian terhadap laki-laki juga tampak ditanamkan, misalnya, pada buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, berjudul Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (2004). Pada sampul belakang buku ini ditulis:
“Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriakhisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan.”
Karena berangkat dari semangat ’kebencian’ dan ’dendam’ inilah maka para pengusung dan pengasong paham kesetaraan gender ini terkadang menjadi gelap mata dan membabi buta dalam upaya merombak hukum-hukum Islam. Mereka memandang hukum-hukum Islam yang membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita perlu ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori ”bias gender” dan menindas perempuan. Seperti sedang melampiaskan ’dendamnya’ buku Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah terbitan PSW UIN Yogya ini pun lalu membongkar ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum Muslimin sebagai satu Ijma’ dari generasi ke generasi. Hampir tidak ada aspek hukum yang luput dari gugatan kaum aktivis gender dari UIN Yogya. Dalam aspek ibadah misalnya, dipersoalkan: mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa dibedakan cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum laki-laki dan makmum wanita; mengapa shaf wanita harus di belakang; mengapa imam dan khatib shalat Jumat harus laki-laki.
Masih dalam aspek ibadah, digugat juga persoalan pembedaan jumlah kambing aqidah bagi anak laki-laki dan wanita. Dalam masalah haji, digugat keharusan wanita ditemani oleh mahramnya, sedangkan laki-laki tidak. Juga, dipersoalkan pembedaan pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Dalam urusan rumah tangga, digugat keharusan istri untuk meminta izin suami jika hendak keluar rumah. Dalam masalah pernikahan, misalnya, digugat juga ketiadaan hak talak bagi wanita. ”Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri, artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami.” (hal. 175). Tak hanya itu, buku ini juga menggugat tugas seorang Ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Ditulis dalam buku ini:
”Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.” (hal. 42-43).
Beginilah cara berpikir kaum gender di lingkungan UIN Yogya. Kita bisa bertanya kepada kaum gender itu, jika menyusui anak bukan tugas wanita, lalu untuk apa Allah mengaruniai wanita dengan sepasang payudara? Bukankah sudah begitu banyak penelitian yang menyebutkan manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi si bayi, bagi si ibu, dan juga bagi hubungan psikologis antara bayi dan ibunya. Tapi, dengan alasan ’kesetaraan gender’, tugas menyusui bagi wanita itu ditolak dan dinyatakan sebagai kewajiban bersama antara bapak dan ibu. Jika perlu, anak disusui dengan botol.
Fenomena Barat dan Kristen
Di dalam buku berjudul Pengantar Kajian Gender terbitan PSW-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003) dikutip sejumlah definisi gender:
”Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinctition) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender: An Introduction sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar (1999), gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men).” (hal. 54).
Para pegiat gender ini biasanya menggugat apa yang mereka sebut sebagai budaya patriarki dalam masyarakat, sebagaimana ditulis dalam buku terbitan PSW-UIN Jakarta: ”Di dalam budaya patriarki ini, bidang-bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan juga di ranah domestik senantiasa dikuasai laki-laki. Sebaliknya, pada waktu yang sama, perempuan terpinggirkan karena perempuan dianggap atau diputuskan tidak layak dan tidak mampu untuk bergelut di bidang-bidang tersebut.” (hal. 60).
Jika ditelaah, sebenarnya, cara pandang ‘gender equality’ tidak terlepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Belakangan, mereka kemudian bergerak dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lain dalam memperlakukan wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, dalam bukunya World Civilizations, (terbit tahun 2000), menggambarkan bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Sampai abad ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. (Mungkin ini terpengaruh oleh konsep Kristen tentang Eva yang digoda oleh Setan sehingga menjerumuskan Adam) Sejak awal penciptaannya, wanita memang sudah tidak sempurna. Mengutip seorang penulis Jerman abad ke-17, Adler menulis: It is a fact that women has only a weaker faith (In God). Adalah fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu, kata mereka, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yang dalam bahasa mereka disebut ‘female’ berasal dari bahasa Yunani ‘femina’. Kata ‘femina’ berasal dari kata ‘fe’ dan ‘minus’. ‘Fe’ artinya ‘fides’, ‘faith’ (kepercayaan atau iman). Sedangkan ‘mina’ berasal dari kata ‘minus’, artinya ‘kurang’. Jadi ‘femina’ artinya ‘seseorang yang imannya kurang’ (one with less faith). Karena itu, kata penulis Jerman abad ke-17 itu: Therefore, the female is evil by nature. (Karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat). 6
Masyarakat Barat seperti terjebak dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan yang tiada ujung pangkal dalam soal nilai. Mereka berangkat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Dalam kasus homoseksual, dulu mereka memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan sadis. Robert Held, dalam bukunya, Inquisition, (Florence: Bilingual publishers, 1985), memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Dalam buku ini juga digambarkan, bahwa pelaku homoseksual digergaji hidup-hidup. Dalam kasus gerakan feminisme Barat juga terjebak ke dalam titik-titik ekstrim. Jika dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita.
Kaum feminis juga berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lagi menulis God, tetapi juga Goddes. Sebab, gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka ingin Tuhan yang perempuan. Dalam buku “Feminist Aproaches to The Bible”, seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah dengan judul: “Goddesses: Biblical Echoes”. Aktivis lain, Pamela J. Milne, mencatat, bahwa dalam tradisi Barat, Bible manjadi sumber terpenting bagi penindasan terhadap perempuan. Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku The Women’s Bible, dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan perempuan, dan dari ajaran inilah terbentuk dasar-dasar pandangan Kristen terhadap perempuan. Berikutnya, Stanton berusaha meyakinkan, bahwa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ajaran Bible. Para tokoh agama Kristen kemudian memandang karya Elizabeth C. Stanton sebagai karya setan. 7
Pemberontakan besar dalam soal posisi dan peran wanita dalam Kristen dilakukan oleh Dan Brown melalui novelnya “The Da Vinci Code”. Novel ini menggugat asas ajaran Kristen, yakni persepsi tentang Jesus sebagai Tuhan. Brown berusaha meyakinkan jutaan pembaca novel ini, bahwa Jesus telah menikahi Mary Magdalena dan mempunyai keturunan. Bukan hanya itu, Jesus juga mewariskan Gerejanya kepada Magdalena dan bukan kepada St. Peter, seperti dipercayai kaum Kristen saat ini. Brown menyodorkan data dari Injil Philip, bahwa Jesus memang mengawini Mary Magdalena dan mempunyai anak keturunan. Di Gospel of Philip tertulis: “And the companion of the Saviour is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, “Why do you love her more than all of us?”
Jadi, kata Bible ini, Jesus mempunyai pasangan bernama Mary Magdalena dan terbiasa mencium Magdalena di bibirnya. Jesus mencintai Magdalena lebih dari pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Itulah yang akhirnya memicu pelarian Mary Magdalena dari Jerusalem ke Perancis dengan bantuan orang-orang Yahudi. Martin Lunn, melalui bukunya, Da Vinci Code Decoded (diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Isma B. Koesalamwardi), mengungkap sejumlah bukti tambahan tentang perkawinan Jesus dengan Mary Magdalena.
Dalam diskursus “gender equality” saat ini, wacana tentang pewarisan Gereja oleh Jesus kepada seorang wanita tentu saja sangat menarik. Sebab, hingga kini, Gereja Katolik tetap tidak mengizinkan wanita ditahbiskan menjadi pelayan gereja. Hingga kini, wanita menjadi warga ‘kelas dua’ dalam Gereja Katolik. Menyusul perdebatan sengit masalah ini, tahun 1994, Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan deklarasi “Ordinatio Sacerdotalis” yang menegaskan: “Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman.”
Begitu juga dengan doktrin “larangan menikah bagi pastor” (celibacy), masih tetap dipertahankan, meskipun sekarang mulai banyak teolog Katolik yang menggugat larangan kawin ini. Prof. Hans Kung, misalnya, melalui bukunya, The Catholic Church: A Short HIstory (New York: Modern Library, 2003), menyebut doktrin celibacy bertentangan dengan Bible (Matius, 19:12, 1 Timotius, 3:2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi salah satu sumber penyelewengan seksual di kalangan pastor. Pendukung novel Dan Brown tentu akan setuju dengan gagasan Prof. Hans Kung dan ide bolehnya wanita menjadi pastor. Logikanya, jika Jesus saja kawin dan mewariskan Gerejanya kepada wanita, maka mengapa pengikutnya dilarang kawin dan melarang wanita menjadi pastor.
Hermeneutika feminis
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu cara pemberontakan kaum feminis terhadap doktrin-doktrin Kristen yang dinilai menindas wanita adalah dengan merombak metode penafsiran Bible, yang dikenal sebagai metode hermeneutika feminis. Kaum feminis Kristen menggunakan metode ini untuk mengubah ketentuan-ketentuan agama Kristen yang mereka pandag menindas kaum wanita. Sebuah buku berjudul Metode Penafsiran Alkitab, yang ditulis Dr. A.A. Sitompul dan Dr. Ulrich Beyer, menjelaskan masalah hermeneutika kaum feminis ini.
Berikut ini ringkasan hermeneutika feminis yang disarikan dalam buku tersebut. Dijelaskan, bahwa metode penafsiran ala feminisme memang belakangan ini berkembang di kalangan Kristen. Asumsi utama yang muncul disebabkan teks Alkitab yang ditulis dalam konteks budaya patriarkal yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam budaya patriarkal pula. Konteks patriarkal ini telah menyebabkan wanita menjadi terdehumanisasi dan menjadi terpinggirkan, serta memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua yang inferior. Semua penafsiran feminis berusaha mengurangi sistem patriarkal tidak saja teks Alkitabiah tetapi juga tradisi teologi yang didasarkan pada teks patriarkal.
Prinsip hermeneutika feminis: (1) Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan wanita sama dengan pria, (2) Semua wanita adalah manusia seutuhnya, (3) Karena wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri.
Dalam analisis Fiorenza, yang terjadi selama ini adalah pelecehan terhadap wanita dengan memakai teks Alkitab sebagai alat untuk menghadang perjuangan wanita menuju kebebasan. Karena itu, suatu hermeneutika feminis menentang kuasa teks patriarkal dan pemakaian mereka sebagai alat menentang perjuangan wanita. Dia lalu mengusulkan lima unsur kunci dalam hermeneutika feminis: (1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa Alkitab; (2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada koreksi. Artinya, banyak teks dan penafsiran harus ditolak jika teks-teks tersebut diabadikan dan mensahkan struktur patriarkal; (3) Penafsiran adalah terpisah dari proklamasi atau pemberitaan Firman Tuhan. Teks atau tradisi yang mengabadikan struktur penindasan patriarkal dilarang diproklamasikan sebagai “firman Allah” untuk bangsa-bangsa pada masa kini. Sebelum teks diterjemahkan dengan bahasa yang inklusif, suatu proses seleksi yang cermat harus dilakukan; (4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarkal akan penindasan harus diubah. Hermeneutika ini bertujuan untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Kristen mula-mula dari perspektif wanita; (5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritus, mengaktualisasikan teks kepada situasi masa kini. Cerita Alkitab diceritakan kembali dari perspektif imajinasi feminis, khususnya sisa-sisa non-patriarkal.
Jadi, yang penting dalam penafsiran feminisme adalah bagaimana teks Alkitab ditafsirkan secara benar tanpa melupakan nilai kemanusiaan seutuhnya. Untuk itu diperlukan studi kritis secara sastra Alkitab maupun dari perspektif yang lain agar penafsiran itu berlangsung secara tepat. 8
Menjiplak Metode Bibel
Jika ditelaah, banyak metode penafsiran kaum feminis terhadap al-Quran sebenarnya merupakan jiplakan terhadap metodologi serupa kaum feminis dalam Kristen dalam menafsirkan Bibel. Di sini ada dua masalah yang perlu ditelaah dengan cermat. Pertama, validitas dan kebenaran konsep ‘gender equality’ itu sendiri. Kedua, perbedaan sifat antara teks Al-Quran dan teks Bible.
PERTAMA, masalah konsep ‘gender equality’ yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam – seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan sebagainya – saat ini sudah terbukti merupakan konsep yang kebablasan dan membubarkan syariat Islam. Konsep ini berangkat dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fithri dan jasadiah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi pembedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita.
Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak. Olah raga merupakan contoh yang jelas, bahwa pria dan wanita memang berbeda. Cabang olah raga tinju, sepakbola, gulat, bulun tangkis, dan sebagainya, membedakan antara kelompok wanita dan kelompok pria. Wanita ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah dari kelas pria. Kaum feminis tidak protes dan meminta agar dalam cabang-cabang olah raga itu mereka disejajarkan dengan pria. Mereka tidak merasa terhina dengan diskriminasi semacam itu. Tetapi, orang seperti Amina Wadud, merasa terhina karena tidak boleh khutbah Jumat dan dalam shaf shalat harus berada di belakang laki-laki.
Jika konsep ‘gender equality’ dijadikan sebagai standar berpikir dalam menafsirkan teks al-Quran, maka akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran. Itulah, misalnya, yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawan. Tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertajuk “Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”. Buku ini telah menjadi perdebatan hebat di Indonesia, sebab untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, sekelompok cendekiawan dari kalangan Muslim yang concern terhadap masalah gender equality dan berada di bawah naungan Departemen Agama mengeluarkan legal draft yang sangat kontroversial. Diantara pijakan pembuatan buku ini ialah paham Pluralisme Agama, disamping konsep gender equality.
Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi hebat diantaranya: Pertama, bahwa asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). Kedua, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Artinya, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut – meskipun keduanya sudah baligh – tetap dinyatakan tidak sah. Ketiga, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54). Keempat, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan rasyid/rasyidah. (pasal 7 ayat 2). Kelima, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri. (pasal 9). Keenam, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). Ketujuh, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). Kedelapan, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).
Konsep kesetaraan gender adalah salah satu agenda penting dari Liberalisasi Islam. Seperti ditulis Budhy Munawar-Rachman, aganda-agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender adalah: (1) Menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (freedom of choice) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, (2) Perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan. 9
KEDUA, masalah perbedaan sifat antara teks al-Quran dan teks Bible. Perbedaan sifat yang mendasar antara teks al-Quran dan Bibel ini biasanya diabaikan oleh kaum feminis. Metode kontekstualisasi yang mengabaikan teks biasa dilakukan dalam tradisi Bible, karena teks Bible memang bukan merupakan teks wahyu. Dalam buku berjudul Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model, karya David J. Hesselgrave dan Edward Rommen (terj. Stephen Suleeman), yang diterbitkan oleh penerbit Kristen, BPK, dijelaskan tentang perbedaan antara karakter teks Bible dengan teks al-Quran. Ditulis dalam buku ini:
“Para pelaku kontekstualisasi Islam diperhadapkan dengan serangkaian masalah yang unik. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kitab yang “dibuat di sorga” dalam bahasa Allah dan tidak mengakui unsur manusia sedikit pun? Kitab itu boleh disampaikan, ditafsirkan, dikhotbahkan, diajarkan, dihafalkan, namun tidak boleh diterjemahkan. Orang Islam berkata bahwa Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain bukanlah Quran yang sesungguhnya.” 10
Dalam keyakinan kaum Muslim, al-Quran – lafadz dan maknanya – adalah dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Termasuk dari Nabi Muhammad saw sendiri. Karena Rasulullah saw senantiasa memisahkan, mana yang merupakan teks al-Quran yang berasal dari wahyu, dan mana yang ucapan beliau sendiri (hadits Nabi). Dalam buku Kontekstualisasi itu juga disimpulkan keyakinan kaum Muslimin seperti itu:
“Memang Allah telah berbicara melalui sejumlah nabi, tetapi dalam menyatakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, Ia memberikan firkman-Nya yang terakhir. Firman itu adalah firman Allah, Nabi Muhammad hanyalah penerima atau pencatat yang pasif. Pikiran, hati, perasaannya – tak satu pun dari semua ini yang masuk ke dalam pencatatan kata-kata al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dan tidak dibuat, yang telah ada sepanjang masa sebagai ungkapan kehendak-Nya. Lebih lanjut, mengingat kerusakan yang dialami pernyataan-pernyataan sebelumnya, Allah berusaha menjamin bahwa pernyataan akhir ini tidak akan rusak sampai selamanya.” 11
Dalam kondisi al-Quran sebagai teks wahyu, maka hampir menutup kemungkinan adanya kontekstualisasi. Di kalangan Kristen, menurut buku ini, hampir tidak ada orang Kristen yang yang berpikiran mirip dengan orang Islam, yakni bahwa teks Bible adalah sepenuhnya merupakan teks wahyu. Hills (1956), misalnya, berpikir tentang pelestarian Alkitab oleh Allah melalui Gereja Yunani, dengan menjadikan teks Byzantium sebagai ‘Textus Receptus’ (Teks yang umumnya diterima), dan kemudian terjemahannya ke dalam bahasa Inggris dikenal sebagai King James Version (1611). Karena itu, Bible King James Version dianggap sebagai satu-satunya terjemahan dalam bahasa Inggris yang berwibawa. 12
Tentang klaim Hills semacam itu, buku ini memberi komentar:
“Meskipun motivasi Hills baik, jelas bahwa pandangannya jauh melampaui tuntutan Alkitab dan kekristenan historis tentang kewibawaan Alkitab. Pandangannya sangat terbuka terhadap kritik dari dalam dan dari luar tradisi Kristen. Lagi pula pandangan ini hampir menutup kemungkinan untuk kontekstualisasi.’’ 13
Berbeda dengan al-Quran, Bible memang ditulis oleh para penulis Bible, yang menurut konsep Kristen, mendapat inspirasi dari Tuhan. Meskipun demikian, diakui, bahwa unsur-unsur personal dan budaya berpengaruh terhadap para penulis Bible. Karena yang dianggap merupakan wahyu Tuhan adalah makna dan inspirasi dalam Bible – dan bukan teks Bible itu sendiri – maka kaum Kristen tetap menganggap terjemahan Bible dalam bahasa apa pun adalah firman Tuhan (dei verbum). Dalam tradisi penafsiran Bible, sebagian teolog melalukan kontekstualisasi yang ekstrim, seperti Bultmann, yang menganggap Bible sebagai mitos. Dengan ini, hampir setiap bentuk kontekstualisasi adalah mungkin, karena ada banyak cara untuk memahami sejarah. 14
Dengan karakter Bible semacam itu, maka para pengaplikasi hermeneutika untuk al-Quran senantiasa — baik secara terbuka atau tidak — berusaha menempatkan posisi dan sifat teks al-Quran sebagaimana halnya teks Bible. Bahwa, teks al-Quran adalah teks budaya, teks yang sudah memanusiawi, dan sebagainya. Salah satu pelopor usaha ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa al-Quran adalah ‘produk budaya’ (muntaj tsaqafi/cultural product). 15
Dengan menempatkan posisi teks al-Quran setara dengan teks Bible, dan memasukkan unsur konteks budaya dan sosial dalam penafsiran teks al-Quran, maka yang terjadi adalah pembuangan makna asal teks itu sendiri. Jika al-Quran diakui sebagai teks wahyu, maka makna yang dikandungnya adalah makna universal. Dan penafsiran al-Quran harus berangkat dari pemahaman terhadap makna teks itu sendiri. Sebaliknya, metodologi kontekstualisasi yang dilakukan para pengaplikasi hermeneutika al-Quran, justru akhirnya lebih berpegang pada konteks dengan meninggalkan teks wahyu itu sendiri.
Sebagai contoh, larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-Muslim dalam QS Mumtahanah:10, yang dengan tegas menyatakan:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”
Tetapi, dengan pendekatan kontekstualisasi, makna ayat tersebut bisa berubah total. Aktivis gender dan Pluralisme Agama, Musdah Mulia, menulis tentang ayat ini:
“Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar
mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan dengan sendirinya.” 16
Argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Dengan logika semacam itu, maka ketika damai, seorang Muslimah halal menikah dengan laki-laki kafir. Lalu, ketika perang, nikahnya jadi haram. Dan jika damai lagi, maka nikahnya halal lagi. Bayangkan, nikahnya Yuni Shara dengan Henry Siahaan, atau Deddy Corbuzier dengan Kalina. Kedua istri itu mengaku berAgama Islam. Ketika Perang Muslim-Kristen meletus di Maluku, pada waktu pagi hari, maka pernikahan mereka haram. Jika sore harinya sudah damai, maka pernikahan mereka jadi halal. Sebab, halal-haramnya tergantung konteks, bukan tergantung teks.
Argumentasi “kontekstual” semacam ini juga bisa menjadi pemikiran yang “liar”. Contoh: “Mengapa daging babi diharamkan?” Maka, harus dilihat konteksnya, bukan hanya teksnya. Secara sosio-ekonomis, daging babi haram, karena babi adalah binatang langka di Arab ketika ayat itu diturunkan. Padahal, babi saat ini adalah binatang yang paling menguntungkan jika diternakkan. Karena itu, secara “kontekstual” sosio-ekonomis, ternak babi adalah halal saat ini, karena sangat maslahat bagi umat Islam. Mengapa khamr haram? Secara kontekstual, Arab adalah daerah panas. Maka, wajar khamr diharamkan. Jika konteksnya berubah (udara dingin), khamr bisa saja halal.
Sepanjang sejarah Islam, banyak kondisi dimana kaum Muslim tidak berperang dengan kaum kafir. Bahkan, selama 1200 tahun lebih, kaum Yahudi hidup damai di dalam wilayah Islam. Tetapi, selama itu pula para ulama tidak pernah berpikir, bahwa QS 60:10 itu ada kaitannya dengan peperangan, sehingga halal saja muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi, karena tidak ada peperangan antara Yahudi dengan Muslim.
Contoh lain yang sangat fatal dalam penafsiran model konteks-sejarah semacam ini dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Semarang dalam soal mahar. Rokhmadi, M.Ag., dosen Syariah IAIN Semarang itu, ditanya tentang kasus perkawinan seorang laki-laki dengan wanita Minang, yang menurut si penanya, maharnya justru diberikan oleh pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Maka dosen itu menjawab:
“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan martabat keluarga. Maka saudara MH Tidak perlu risau, susah, dan gelisah. Justru saudara beruntung tidak dibebani Mahar. Terimalah, sebab ketentuan al-Quran (al-Nisa ayat 4) tidak bersifat mutlak karena semata-mata dipengaruhi budaya di mana Islam diturunkan.17
Penutup
Dari paparan terdahulu tampak bagaimana kecerobohan kaum feminis di kalangan Muslim dalam menjiplak – sadar atau tidak – metodologi penafsiran Bible di kalangan feminis Kristen. Mereka tidak menyadari akan hakekat perbedaan sifat antara teks Bible dan teks al-Quran sehingga menyamakan begitu saja metodologi penafsirannya. Kedua, mereka sendiri terjebak dalam ‘pra-pemahaman’ subjektif dari konsep ‘gender equality’ sekular-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam. ‘Keadilan’ menurut Islam, misalnya, bukanlah sama-rata sama-rasa. Laki-laki dan wanita, bagaimana pun, tidak sama.
Para pengusung paham kesetaraan gender ini mungkin lupa, bahwa syariat Islam bersifat universal, yang bersifat lintas zaman dan lintas budaya, karena Nabi Muhammad saw adalah Nabi yang diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum atau bangsa tertentu sebagaimana Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.
‘’Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) kecuali kepada seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya.’’ (QS 34 :28).
Karena sifatnya yang universal inilah, maka akan sangat keliru jika dalam penafsiran al-Quran justru dikedepankan metode kontekstual sejarah, sebagaimana yang diterapkan oleh kaum Yahudi dan Kristen liberal. Harusnya, para feminis itu membangun kerangka berfikirnya dari pandangan hidup Islam (Islamic worldview), yang tersusun atas konsep-kosep dasar Islam tentang Tuhan, manusia, kebenaran, ilmu, kenabian, wahyu, dan sebagainya. Jika worldview para feminis itu sudah terkooptasi oleh ‘worldview’ bukan Islam, maka dia otomatis akan meletakkan Islam dan al-Quran dalam kerangka pikir yang bukan Islam. Dan itulah akibatnya. Mereka akhirnya berani meninggalkan dan membuat hukum-hukum baru yang bertentangan dengan makna sebenarnya dari nash-nash al-Quran dan Sunnah Rasul.
Para feminis menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender. Tuduhan itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat mereka keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk meindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki atas wanita, merupakan kecurigaan yang bias gender. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama wanita dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.
Sebagai contoh, ulama fiqih wanita terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa’id Fayiz al-Dukhayyil, Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, HayÉtihÉ wa FiqhihÉ, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan wanita Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dari kalangan Muslim, yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.
Yang diperlukan adalah satu perspektif yang benar dan ikhlas dalam menerima pembagian peran yang diberikan oleh Allah SWT. Jika wanita diberikan peran utama sebagai ‘rabbatul bayt’ (pengelola rumah tangga) dan laki-laki sebagai pencari nafkah, hal itu bukanlah suatu penistaan terhadap wanita. Sebab, dunia ini hanyalah satu ‘panggung sandiwara’. Setiap kita mengambil satu peranan yang nantinya akan sama-sama dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat. Maka, ada baiknya, kita renungkan lagu berjudul ‘Dunia Ini Panggung Sandiwara’, yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1976, dan kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Albar :
Dunia ini panggung sandiwara
Ceritanya mudah berubah
Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani
Setiap insan dapat satu peranan
Yang harus kita mainkan
Ada peran yang wajar dan ada peran berpura-pura
Mengapa kita bersandiwara?
Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak
Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang
Dunia ini penuh peranan
Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan
Mengapa kita bersandiwara?
Ya… Dunia ini adalah panggung sandiwara. Allah yang mengatur semuanya. Setiap kita, laki-laki atau perempuan, mendapatkan peranan sesuai dengan fitrahnya. Bahkan, ada manusia yang dulu diberi peranan sebagai budak. Ada yang berperan sebagai manusia merdeka. Ada yang berperan sebagai manusia cacat, bisu, dan tuli. Ada yang berperan sebagai orang pintar dan kaya. Allah SWT lebih tahu apa fitrah manusia. Jika perempuan dipoligami, bukan dia sedang ditindas oleh laki-laki. Karena di akhirat nanti, dia akan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Jika laki-laki berpoligami, maka tanggung jawabnya akan semakin berat di dunia dan akhirat. Ia harus melaporkan tanggung jawabnya atas semua istrinya.
Jika perempuan menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti dia lebih rendah derajatnya dibandingkan perempuan yang menjadi menteri atau Presiden. Di akhirat, perempuan yang menjadi menteri akan lebih berat tanggung jawabnya. Dia bukan hanya harus melaporkan kepada Allah atas kehidupan rumah tangganya, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebagai menteri, belum tentu dia bahagia di dunia. Lihatlah, kadangkala, kita lihat untuk tersenyum pun sudah sulit, karena dibelit berbagai permasalahan pekerjaan. Di akhirat, tentu saja tanggung jawabnya semakin berat.
Karena itu, jika Allah tidak mewajibkan perempuan mencari nafkah, tidak wajib shalat Jumat, dan sebagainya, bukan berarti Allah menghinakan perempuan. Justru, Allah sayang kepada perempuan. Dengan diberikan beban yang sedikit, perempuan sudah dapat menggapai pintu sorga. Jika kesaksian perempuan dihargai setengah laki-laki dalam urusan kriminal, justru itu lebih meringankan perempuan. Sebab, menjadi saksi bukanlah pekerjaan yang mengenakkan. Tanggung jawabnya berat. Salah-salah sedikit bisa terseret menjadi tersangka.
Perspektif akhirat inilah yang harus digunakan dalam melihat berbagai masalah, agar hati menjadi tenang dan bahagia. Jika tidak, maka seorang perempuan dapat merasa terhina karena menyediakan minuman bagi suaminya. Dia bisa berpikir, ”Mengapa bukan dia yang melayani saya, padahal gaji saya lebih besar dari dia?” Jika dia akan keluar rumah, dia merasa dibebani karena diharuskan meminta izin kepada suaminya. Dia bisa berkata: ”Mengapa harus saya meminta izin. Mengapa bukan suami yang minta izin?”
Gugatan-gugatan semacam ini akan semakin panjang untik dilontarkan. Ketika konsep ”kesetaraan” ala Barat diyakini dan dijadikan sebagai ”framework” dalam melihat segala aspek hubungan laki-laki dan perempuan, maka akan bubarlah konsep keluarga dan sosial dalam Islam. Atau, apakah ini yang memang dimaui oleh kaum Marxis dan kaum feminis liberal?
Harusnya para aktivis organisasi Islam bertanya pada hatinya yang paling dalam, ”Mengapa AS dan sekutu-sekutunya begitu royal memberikan bantuan untuk merombak pemikiran dan tatanan keluarga kaum Muslim?” Apakah mereka begitu sayang kepada umat Islam dan secara tulus ikhlas menginginkan kemajuan umat Islam?
1 Amina Wadud, Quran Menurut Perempuan, hal. 33. Tahun 2004, PSW UIN Yogya menerbitkan sebuah buku berjudul Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, yang juga berpijak pada konsep relativisme Tafsir: ”Teks-teks keagamaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa dipahami, kecuali dalam relasinya dengan entitas lainnya. Pada tataran inilah pentingnya kita melihat kembali teks dan pemahaman serta penafsirannya secara epistemologis dan hermeneutis. Bila ini sudah dilakukan, maka penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Quran dan hadis, terasa bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, tapi malah sebagai keniscayaan. Mengapa menjadi niscaya, karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang ”tabu” dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena siapa tahu jika yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dogma agama itu – dalam istilah Peter L. Berger dan Luckmann – adalah sesuatu yang bersifat socially constructed belaka.” (hal. 2)
2Ibid, hal. 158. Praktik dan gagasan Amina Wadud ini kemudian dipuji-puji kaum liberal di Indonesia. Husein Muhammad, seorang aktivis kesetaraan gender, mendukung keabsahan wanita menjadi imam bagi laki-laki. Menurut Husein Muhammad, pandangan yang mengharamkan wanita menjadi imam salat bagi laki-laki, muncul dari masyarakat yang memiliki budaya patriarki. Ia menulis: “Maka kehadiran dan penampilan perempuan di hadapan laki-laki apalagi dalam shalat, dianggap atau diyakini bisa mengganggu pikiran dan hati laki-laki pada umumnya. Pandangan ini sesungguhnya muncul dari mainstream kebudayaan laki-laki atau yang seringkali disebut pandangan kebudayaan patriarki.” (Lihat, Husein Muhammad, “Perempuan dalam Fiqh Ibadah”, dalam buku Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah, terbitan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2005), hal. 22)
3Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? (Bandung: Mizan, 1999), hal. 11.
4Ibid, hal. 9-10.
5M. Idrus Ramli (ed.), Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, Pasuruan, 2004. Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis “Kesetaraan Gender” yang tergabung dalam forum FK3.
6Philip J. Adler, World Civilization, (Belmont: Wasworth, 2000), hal. 289.
7Phyllis Trible (et.al.), Feminist Aproaches to The Bible, (Washington: Biblical Archeology Society, 1995).
8A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, Metode Penafsiran Alkitab, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hal. 337-340.
9Budhy Munawar Rachman, “Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia”, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 75.
10David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hal. 169.
11Ibid, hal. 168.
12King James di sini adalah Raja Inggris yang dikenal dengan nama Stuart King James VI of Scotland, dan menjadi King James I of England. Dia seorang yang kontroversial. Pada satu sisi, atas jasanya memelopori penulisan Bible “King James Version”, ia sangat dihormati dan mendapatkan julukan yang sangat mulia sebagai “Defender of Faith”, “Sang Pembela Agama”. Namun, sejarawan Barat, seperti Philip J. Adler, menyebutnya sebagai seorang yang arogan dan pelaku homoseks yang terang-terangan (blatant homosexual).
13David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model, hal. 174-175.
14Tentang perbedaan antara al-Quran dan Bible, Dr. C. Groenen OFM membuat deskripsi menarik: Bahwa Bible (yang diperkirakan ditulis antara kurun waktu sekitar tahun 40-120 M) merupakan kitab suci yang diinspirasikan oleh Allah. “Kadang-kadang “inspirasi” itu diartikan seolah-olah Allah “berbisik-bisik “ kepada penulis. Seolah-olah Allah mendiktekan apa yang harus ditulis. Lalu orang berkata bahwa Kitab Suci mirip dengan “suatu rekaman”. Boleh jadi saudara-saudara muslimin dapat memahami kiasan macam itu sehubungan dengan Al-Quran. Tetapi ucapan itu kurang tepat kalau dipakai sehubungan dengan Alkitab umat Kristen. Sejarah terbentuknya Alkitab memustahilkan kiasan macam itu. Adakalanya orang sampai menyebut Kitab Suci sebagai “surat Allah kepada umat-Nya”. Tetapi pikiran itu sedikit kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak dapat dikatakan bahwa (semua) penulis suci “mendengar suara Allah yang mendiktekan” sesuatu. Mereka malah tidak sadar bahwa sedang menulis Kitab Suci!” (C. Groenen, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal. 19-37.
15Michael Cook, dalam bukunya, The Koran: A Very Short Introduction, (2000:44), mengutip pendapat Nasr Hamid – yang dia tulis sebagai “a Muslim secularist” – tentang al-Quran sebagai produk budaya: “If the text was a message sent to the Arabs of the seven century, then of necessity it was formulated in a manner which took for granted historically specific aspects of their language and culture. The Koran thus took shape in human setting. It was a ‘ cultural product’ – a phrase Abu Zayd used several times, and which was highlighted by the Court of Cassation when it determined him to be an unbeliever. (Pendapat Lester dan Cook dikutip dari buku The History of the Qur’anic Text, From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament, karya MusÏafa A’zhami (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), hal. 8-9.
16Musdah Mulia, Muslimah Reformis, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 63.
17Lihat, Jurnal Justisia Fakultas Syariah IAIN Semarang, Edisi 28 Th.XIII/2005.





